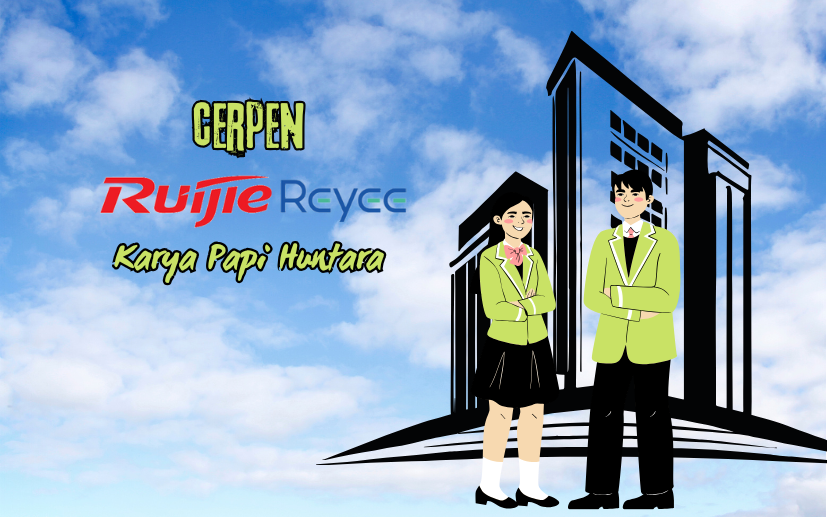Ruijie menatap buku catatan yang tergeletak di atas meja kayu kecilnya. Halaman-halaman kosong itu seakan mengejeknya, menyuarakan kekosongan yang sama seperti yang ia rasakan di dalam hatinya. Di luar, hujan turun dengan rintik-rintik lembut, mengiringi suara angin yang berbisik di sela dedaunan.
Ia baru saja pindah ke apartemen ini, meninggalkan hiruk-pikuk kota dan kenangan yang tak ingin ia ingat. Tapi tetap saja, ada satu kenangan yang menempel erat, tak mau terhapus meski ia mencoba berlari sejauh apapun. Reyee. Nama itu seperti mantra, melompat-lompat di pikirannya setiap malam.
“Ruijie?” suara halus itu menyadarkannya.
Ia menoleh. Di balik pintu kaca, Reyee berdiri, mengenakan mantel cokelat yang sudah basah di bagian bawah. Senyumnya samar, seperti meminta izin untuk masuk.
Ruijie bangkit, setengah tak percaya. “Reyee? Kamu…”
“Aku boleh masuk?” potongnya sebelum Ruijie sempat menyelesaikan kalimatnya.
Ia mengangguk, masih terpaku oleh kehadiran wanita itu. Reyee berjalan masuk, membawa aroma hujan dan sedikit wangi lavender yang selalu ia kenakan.
“Aku tidak tahu kamu di sini,” kata Reyee setelah duduk di sofa kecil yang menghadap ke jendela. “Tetangga bilang ada penghuni baru. Aku tidak menyangka itu kamu.”
Ruijie tertawa kecil, hambar. “Aku tidak tahu kalau kita akan bertemu lagi, jujur saja. Dunia ini terlalu kecil, ya?”
“Atau mungkin ini takdir,” Reyee berbisik, lebih kepada dirinya sendiri.
Ruijie diam. Kata-kata Reyee seperti jarum yang menusuk langsung ke dalam hatinya. Ia ingat bagaimana segalanya berakhir antara mereka. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama. Hanya dua hati yang saling menjauh, seperti lempeng bumi yang bergeser perlahan-lahan, tetapi cukup untuk menciptakan gempa besar di antara mereka.
“Kenapa kamu datang ke sini?” tanya Ruijie akhirnya.
“Aku tidak tahu,” jawab Reyee. “Mungkin… aku hanya ingin melihat kamu lagi. Setelah semua waktu ini.”
Ruijie mengerutkan dahi. “Lalu? Apa yang kamu harapkan, Reyee? Aku bukan orang yang sama lagi.”
Reyee tertawa kecil, tetapi suaranya terdengar getir. “Siapa yang sama setelah apa yang kita lalui, Ruijie? Aku juga berubah.”
Hening menggantung di antara mereka, seperti jeda panjang dalam sebuah simfoni. Ruijie ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sebaliknya, ia hanya menatap wajah Reyee yang masih terlihat sama seperti dulu—cantik, tetapi kini dihiasi dengan kelelahan yang sulit disembunyikan.
“Aku menyesal,” kata Reyee akhirnya.
Ruijie mendongak, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. “Menyesal?”
Reyee mengangguk. “Bukan karena aku meninggalkanmu, tetapi karena aku tidak pernah memberimu alasan yang cukup. Aku pikir itu akan lebih mudah untukmu jika aku pergi begitu saja, tanpa penjelasan. Tapi aku salah.”
“Ya, kamu salah,” potong Ruijie, nadanya tajam. “Kamu meninggalkan aku dengan seribu pertanyaan. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba mencari tahu apa yang salah. Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku membuatmu kecewa?”
“Aku takut,” Reyee mengaku, suaranya bergetar. “Aku takut kita terlalu sempurna, terlalu bahagia. Aku takut suatu hari semua itu akan runtuh dan kita akan saling menyakiti. Jadi aku memilih untuk pergi sebelum itu terjadi.”
Ruijie tertawa getir, penuh rasa pahit. “Kamu takut sesuatu yang belum tentu terjadi? Itu alasanmu?”
“Ya,” jawab Reyee dengan tegas. “Dan aku tahu itu pengecut. Tapi itulah aku. Aku pengecut, Ruijie. Dan aku menyesalinya setiap hari.”
Ruijie berdiri, berjalan ke arah jendela. Hujan semakin deras, menambah nuansa melankolis dalam ruangan itu. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan gejolak di dadanya.
“Apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini, Reyee?” tanyanya tanpa menoleh. “Kamu ingin aku memaafkanmu? Atau kamu ingin aku mengatakan bahwa aku baik-baik saja?”
“Aku tidak tahu,” jawab Reyee jujur. “Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih memikirkanmu. Bahwa aku merindukanmu.”
Ruijie membalikkan badan, menatapnya dengan sorot mata yang tajam. “Kamu merindukanku? Setelah semua yang kamu lakukan? Itu tidak adil, Reyee. Kamu pergi, tetapi sekarang kamu ingin kembali hanya karena kamu merindukanku?”
Reyee berdiri, mendekatinya. “Aku tahu ini tidak adil. Aku tahu aku tidak punya hak untuk berharap apa-apa darimu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, Ruijie. Aku mencintaimu. Selalu.”
Kata-kata itu menghantam Ruijie seperti gempa besar, mengguncang seluruh dunia kecilnya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi ia juga tahu bahwa ia masih mencintai wanita itu.
“Kamu tahu, Reyee,” katanya pelan, “kamu seperti lempeng bumi dalam hidupku. Bergeser sedikit saja, kamu sudah mengguncang hatiku. Aku mencoba membangun ulang diriku setelah kamu pergi, tapi sekarang kamu di sini lagi, membawa semua kenangan itu kembali.”
“Aku tidak ingin menghancurkanmu lagi,” bisik Reyee, air mata mulai mengalir di pipinya. “Aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya.”
Ruijie menghela napas panjang. “Kamu pikir mudah bagiku untuk percaya lagi setelah semua ini? Kamu pikir aku bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi?”
“Tidak,” jawab Reyee. “Aku tidak berharap itu mudah. Aku hanya berharap kamu mau mencoba.”
Mereka berdiri di sana, saling menatap, sementara hujan terus turun di luar. Dalam hati Ruijie, ada pertempuran besar antara rasa sakit masa lalu dan harapan untuk masa depan.
Akhirnya, ia berkata, “Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya, Reyee. Tapi aku ingin mencoba.”
Reyee tersenyum, meskipun air mata masih membasahi wajahnya. “Itu sudah lebih dari cukup untukku, Ruijie.”
Mereka duduk bersama di sofa kecil itu, berbagi kehangatan yang selama ini hilang. Di luar, hujan perlahan reda, seakan memberikan restu pada awal baru mereka. Dan meskipun Ruijie tahu perjalanan ini tidak akan mudah, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta mereka masih cukup kuat untuk mengatasi segala gempa yang datang di masa depan.