Deru mesin di ruang produksi PT Sinar Baja Prismatama (SBP) menggema seperti suara badai logam. Di tengah kebisingan itu, Ranto pria 48 tahun dengan wajah keras dan mata selalu tegang berjalan menyusuri lorong. Seragamnya selalu rapi, sepatu selalu mengilap, tapi nada suaranya selalu seperti gergaji: tajam dan menyayat.
“Eh, Minto! Kau tidur lagi, hah?!” suaranya menggema keras, membuat beberapa karyawan menoleh.
Minto, pria 36 tahun yang baru dua minggu bekerja, terperanjat dari kursi ruang istirahat, matanya masih berat. “Maaf, Pak… saya cuma istirahat sebentar, tadi begadang bantu istri jualan nasi”
“Begadang? Itu urusan rumah tangga, bukan urusan kantor! Di sini, yang dibayar itu kerja, bukan ngorok!” bentak Ranto.
Suasana mendadak tegang. Beberapa karyawan saling pandang, lalu pura-pura sibuk.
Dari balik pintu kaca, Frans manajer produksi menghela napas panjang. Ia sudah hafal dengan adegan semacam itu. Hampir tiap minggu ada yang jadi korban omelan Ranto. Meski rajin dan berpengalaman, Ranto terkenal egois, suka menuntut, dan merasa paling benar.
Frans keluar dari ruangannya dengan langkah tenang. “Pak Ranto,” katanya lembut, “boleh kita bicara sebentar di ruangan saya?”
Ranto menatap tajam. “Kalau soal anak itu, saya gak salah, Pak Frans. Disiplin itu wajib, gak peduli dia siapa!”
“Saya tahu,” ujar Frans sabar. “Tapi mari bicara sebentar, biar gak salah paham.”
Ranto menghela napas, lalu berjalan dengan wajah masam.
Di ruang manajer yang sejuk, Santi sekretaris perusahaan sedang menata bunga plastik sambil menelpon. Wangi parfumnya menyeruak ke seluruh ruangan. Usianya 42, berpenampilan rapi dan selalu modis. Suaminya seorang pejabat daerah, dan karena itu, Santi merasa punya kuasa tak tertulis di kantor.
Begitu melihat Ranto, ia tersenyum sinis. “Wah, Pak Ranto lagi-lagi trending ya? Saya dengar tadi sampai tukang parkir di luar tahu Bapak marah-marah.”
“Saya gak marah, cuma menegakkan disiplin,” jawab Ranto ketus.
Frans memberi isyarat agar Santi keluar. Tapi tentu saja, Santi tidak langsung pergi. Ia menatap Ranto dengan gaya menggurui. “Kadang, Pak, terlalu keras itu bikin orang malah malas. Dunia kerja itu bukan tempat perang, tapi tempat saling bantu.”
Ranto mendengus. “Kalau semua lembek kayak kamu, pabrik ini udah bangkrut sejak lama.”
Santi mendelik, tapi Frans memotong cepat, “Santi, tolong buatkan kopi, ya.”
Dengan dagu terangkat, Santi keluar.
Begitu pintu tertutup, Frans duduk berhadapan dengan Ranto. “Pak Ranto, saya tahu Bapak orang lama di sini. Pengalaman Bapak sangat berarti. Tapi kita juga harus tahu batas.”
Ranto mendengus. “Saya cuma ingin semuanya jalan baik. Kalau anak baru seenaknya, nanti rusak sistem, Pak.”
“Setuju,” kata Frans pelan. “Tapi bukan berarti kita kehilangan empati.”
Ranto diam. Matanya menatap jendela yang menampilkan pemandangan pabrik dan langit kelabu. Dalam diamnya, Frans bisa membaca ada sesuatu di balik amarah itu.
Dan benar saja. Ranto tiba-tiba berkata, “Saya tuh stres, Pak. Anak saya minta motor baru, istri ngeluh uang belanja kurang. Saya kerja setengah mati, tapi gaji segini-gini aja. Pantas saya marah kalau lihat orang lain malas.”
Frans menatapnya lama. “Saya paham, Pak. Tapi mencampur urusan rumah dan kantor hanya akan bikin Bapak tambah lelah.”
Ranto terdiam. Ia tidak menjawab, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa nasihat itu menembusnya perlahan, seperti cahaya menembus kabut tebal.
Seminggu kemudian, perusahaan menugaskan beberapa karyawan mengikuti seminar efisiensi produksi di Bandung. Ranto termasuk salah satunya.
Begitu menerima surat tugas dan amplop uang transport, ia langsung menghitung.
“Lho, ini cuma segini?” serunya kepada Santi di depan meja resepsionis. “Saya ke Bandung, bukan ke pasar Senen! Harga bensin naik, makan juga mahal!”
Santi menjawab datar, “Sudah sesuai hitungan perusahaan, Pak. Bahkan lebih dari cukup.”
“Lebih dari cukup dari mana? Saya ini teknisi senior, bukan OB! Kalau OB mungkin iya, cukup buat beli mi instan!”
Santi tersenyum miring. “Kalau merasa kurang, mungkin bisa belajar bersyukur, Pak.”
Ranto menatapnya tajam. “Kamu ngomong apa?”
Frans yang kebetulan lewat langsung menengahi. “Sudah, sudah. Ranto, nanti kalau ada tambahan kebutuhan, kita bicarakan lagi. Jangan di depan umum.”
Ranto memalingkan wajah, tetapi hatinya panas. Di kepalanya hanya ada satu kata: tidak adil.
Di Bandung, seminar berjalan lancar. Tapi begitu kembali ke kantor, Ranto langsung menuntut uang tambahan.
“Transport saya kemarin kurang, Pak Frans,” katanya keras. “Saya keluar uang lebih buat makan dan parkir. Harus diganti.”
Frans membuka laporan dan melihat nota yang diserahkan Ranto. Ada beberapa yang mencurigakan—jumlahnya dilebihkan, bahkan ada nota duplikat.
“Pak Ranto,” ujarnya hati-hati, “sepertinya ini ada yang tidak sesuai.”
Ranto langsung defensif. “Saya gak nipu, Pak! Saya cuma minta hak saya. Jangan pelit!”
Frans menarik napas panjang. “Saya bukan pelit, Pak. Tapi perusahaan harus tertib. Kalau semua mau menambah sendiri, nanti berantakan.”
Wajah Ranto memerah. Ia merasa terhina. Tapi sebelum ia bicara lagi, Frans menambahkan, “Saya harap Bapak bisa memahami. Kita kerja bukan untuk selalu menuntut, tapi juga memberi.”
Ranto tak menjawab. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah berat, dada sesak oleh rasa marah bercampur malu.
Beberapa hari berikutnya, suasana kantor mulai berubah. Ranto jadi lebih pendiam, tapi bukan karena sadar lebih karena kecewa. Ia mulai ogah-ogahan bekerja, sering menatap kosong.
Hingga suatu hari, Darto si OB datang membawa kabar. “Pak Ranto, si Minto kecelakaan kecil, Pak. Tangannya kegores mesin waktu bantu saya pindahkan barang.”
Ranto spontan berdiri. “Kok bisa? Dia belum bisa pakai alat itu!”
“Dia bantu saya karena saya kepepet, Pak. Katanya mau buktiin kalau dia gak malas.”
Ranto bergegas ke klinik pabrik. Di sana, ia melihat Minto duduk menunduk, tangannya diperban.
“Kenapa kamu gak hati-hati?” tanya Ranto, separuh marah, separuh khawatir.
Minto tersenyum kecil. “Saya pengin Bapak gak marah terus, Pak. Saya pengin belajar.”
Kata-kata itu membuat dada Ranto terasa berat. Ia menatap wajah Minto lelaki sederhana, mata tulus, senyum malu-malu. Ranto teringat dirinya dulu, dua puluh tahun lalu, saat baru bekerja dan sering dimarahi senior.
“Saya… dulu juga sering disemprot,” katanya pelan. “Tapi saya belajar juga. Bedanya, dulu ada orang yang sabar ngajarin saya.”
Minto menatapnya heran. “Bapak?”
“Ya. Sekarang mungkin giliran saya yang harus belajar sabar.”
Untuk pertama kalinya, Ranto menepuk bahu Minto. “Istirahatlah. Besok baru masuk.”
Sejak hari itu, perlahan sikap Ranto berubah. Ia tidak lagi mudah marah, meski sesekali masih uring-uringan. Ia mulai belajar memisahkan urusan kantor dari masalah rumah.
Suatu pagi, Darto melihatnya tersenyum saat menyeruput kopi. “Wah, Pak Ranto sekarang adem ya. Tumben gak ada yang kena semprot.”
Ranto tertawa kecil. “Mungkin karena saya udah sadar, Dar. Hidup ini gak selalu harus sesuai maunya kita.”
Santi yang lewat ikut menyahut. “Atau mungkin karena habis dimarahi Pak Frans,” katanya menggoda.
Ranto menoleh sambil tersenyum. “Bisa jadi. Tapi kadang, teguran yang bikin malu justru membuka mata.”
Frans yang mendengar dari ruangannya keluar dan berkata, “Saya cuma ingin semua orang di sini bahagia, termasuk Pak Ranto.”
“Bahagia itu gampang diomong, Pak,” jawab Ranto. “Tapi ternyata cuma butuh satu hal: bersyukur.”
“Setuju,” kata Frans. “Sekecil apa pun syukur itu, bisa menenangkan hati.”
Sore itu, pabrik kembali tenang. Matahari senja menembus jendela, memantul di lantai yang bersih. Minto masih bekerja, menyapu area kerja. Tanpa banyak bicara, Ranto ikut mengambil sapu di sudut ruangan.
“Lho, Pak Ranto bantu saya?” tanya Minto terkejut.
Ranto tersenyum. “Sekecil apa pun kerjaan baik, tetap kerjaan baik.”
Darto yang lewat bersiul. “Wah, dunia kebalik. Dulu yang nyuruh sekarang ikut nyapu!”
Mereka bertiga tertawa. Dari kejauhan, Frans menatap adegan itu dengan rasa lega. Ia tahu, tak ada perubahan yang instan, tapi hari itu, di pabrik kecil itu, cahaya sekecil syukur telah benar-benar mengusir gelap.
Dan di antara bunyi mesin yang tak henti berdengung, terdengar suara hati Ranto sendiri, berbisik pelan:
“Ternyata benar. Sekecil apa pun cahaya, tetap mampu mengusir gelap. Begitu juga syukur, sekecil apa pun ia, mampu menenangkan hati.”
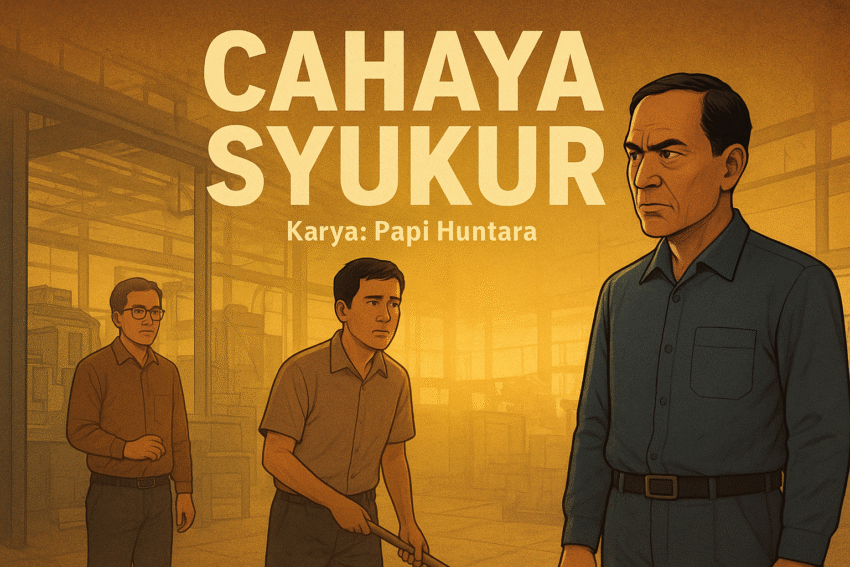
Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam belajar kita harus kita harus sabar, mau bekerja sama serta selalu bersyukur agar hidup lebih tenang
ceritanya sangat seru tampak seperti nyata
ceritanya sangat seru nampak seperti nyata