Jakarta sore itu penuh dengan bunyi klakson, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan, dan angin panas yang membawa debu. Di antara keramaian itu, dua sahabat berjalan dengan langkah berat: Kadir dan Asmuni. Mereka baru saja meninggalkan rumah Doyok, majikan lama yang lebih senang mempermainkan pembantu daripada memperlakukan mereka sebagai manusia.
“Asmuni, lihatlah,” ujar Kadir sambil mengibaskan saputangan kecil di wajahnya. “Kota ini memang keras, tapi aku yakin di balik setiap pintu ada rezeki.”
Asmuni mendengus. “Keras? Rasanya lebih keras dari batu. Kalau begini terus, aku lebih baik balik kampung saja.”
Kadir menepuk bahu sahabatnya. “Jangan menyerah. Kalau becak saja bisa jalan dengan roda reyot, kita juga pasti bisa.”
Belum selesai mereka berdebat, sebuah sedan berhenti di jalanan tak jauh dari mereka. Asap tipis mengepul dari kap mesin, dan dua gadis keluar dengan wajah cemas. Yang pertama, Vivi, berparas lembut dengan rambut hitam panjang tergerai. Yang kedua, Erni, lebih manis dengan senyum malu-malu yang justru memikat siapa pun yang melihatnya.
“Mobil kita mogok,” kata Vivi cemas. “Mas… bisa bantu dorong sampai rumah?”
Kadir langsung mengangguk dengan semangat. “Tentu saja! Dorong mobil? Itu keahlian kami!”
Asmuni sempat ingin protes karena tenaganya sudah nyaris habis, tetapi ketika matanya bersitatap dengan Erni, seluruh keluh kesahnya hilang. Ada sesuatu dalam tatapan itu hangat, jujur, dan membuat dadanya bergetar.
Mereka berdua pun mendorong mobil itu, melewati jalan penuh lubang, menahan tawa ketika sandal Asmuni putus di tengah dorongan. Meski peluh bercucuran, keduanya tersenyum karena merasa sedang menolong seseorang yang berarti. Sampai akhirnya mereka tiba di halaman rumah besar bercat putih dengan pagar besi tinggi.
“Terima kasih banyak,” ucap Vivi tulus. “Kalau tidak ada kalian, kami entah bagaimana bisa pulang.”
Ayah mereka, Kusno, keluar menyambut. Seorang pria tegas dengan wajah yang berwibawa. Ia sempat memandang curiga, tetapi setelah mendengar cerita Vivi dan Erni, ia mempersilakan mereka beristirahat.
Tak lama kemudian, sebagai tanda terima kasih, Kusno menawarkan pekerjaan pada Kadir dan Asmuni. Keduanya menerima tanpa ragu. Bagi mereka, punya tempat tinggal, makanan, dan pekerjaan adalah anugerah besar.
Hari-hari pun berjalan. Kadir dengan sifatnya yang kocak sering menghidupkan suasana rumah. Ia bisa menjatuhkan baskom air hanya karena melihat kucing lewat, atau menyanyi dengan suara sumbang sampai semua orang tertawa. Asmuni lebih pendiam, tapi setiap kali Erni lewat dengan gaun sederhana dan buku di tangan, ia merasa jantungnya berpacu lebih cepat.
Malam-malam di rumah itu sering diisi dengan musik. Erni suka memainkan piano, sementara Vivi kadang menyanyi dengan suara merdu. Kadir biasanya ikut-ikutan bernyanyi meski fals, sementara Asmuni hanya duduk di sudut, menatap Erni dengan penuh harap.
Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Asmuni duduk di teras bersama Kadir. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari halaman.
“Kadir,” bisik Asmuni, “aku… suka Erni. Entah sejak kapan, tapi setiap kali melihat senyumnya, aku merasa hidup ini tidak seburuk yang aku kira.”
Kadir menatapnya serius. “Kau jatuh cinta, Asmuni.”
Asmuni menunduk. “Tapi aku tahu diri. Aku hanya pembantu. Mana mungkin…”
Kadir menepuk bahunya. “Jangan remehkan cinta. Kadang dia melintasi batas yang tidak kita bayangkan. Tapi hati-hati, jangan sampai kau hanya terluka.”
Sayangnya, bisikan itu tidak hanya didengar Kadir. Kusno, yang lewat di koridor, menangkap ucapan Asmuni. Wajahnya muram, dan esok paginya ia memanggil mereka berdua.
“Kalian sudah saya beri pekerjaan,” katanya dengan nada tegas. “Tapi jangan pernah bermimpi yang tidak pantas. Mulai hari ini, kalian tidak perlu bekerja di sini lagi.”
Asmuni merasa seluruh dunia runtuh. Ia menahan air mata, hanya bisa menunduk. Kadir mencoba berbicara, tetapi Kusno sudah berbalik. Mereka pun diusir, kembali ke jalanan.
Namun takdir selalu punya celah. Jojon, salah satu pembantu lama, diam-diam memberi mereka alamat saudaranya, Diran, pemilik bengkel kecil di pinggiran kota. “Pergilah ke sana,” kata Jojon. “Diran orang baik, dia pasti mau menolong.”
Maka dimulailah babak baru. Di bengkel itu, Kadir dan Asmuni bekerja keras. Mereka belajar membongkar mesin, mengganti oli, dan memperbaiki mobil tua. Meski lelah, setidaknya ada arah. Tentu saja kekonyolan tetap terjadi. Suatu kali motor gandengan terlepas di jalan, membuat pengemudi lain kabur ketakutan. Pernah juga ada mobil yang melaju dengan tiga roda karena mereka salah memasang baut. Semua itu membuat mereka tertawa, meski kadang juga kena omel Diran.
Namun di balik semua kesibukan itu, hati Asmuni tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam ia memikirkan Erni. Ia menuliskan namanya di kertas bekas, menggambar bintang, seolah dengan itu ia bisa mendekatkan dirinya pada gadis yang jauh.
Doanya terkabul lebih cepat dari yang ia kira. Suatu siang, saat mengantar surat dari bengkel ke pelanggan, mereka berpapasan dengan Vivi dan Erni di trotoar.
“Mas Kadir! Mas Asmuni!” seru Vivi dengan wajah ceria. “Kami mencarimu. Ayah ingin kalian kembali. Beliau menyesal sudah mengusir kalian. Rumah terasa sepi tanpa kalian.”
Erni berdiri di samping kakaknya, tersenyum malu. Pandangannya bertemu dengan Asmuni hanya sekilas, tetapi cukup membuat hati mereka bergetar.
Kadir menepuk bahu sahabatnya. “Lihat, Asmuni. Roda nasib memang aneh. Kadang oleng, kadang mogok, tapi selalu membawa kita ke tempat yang tepat.”
Mereka pun kembali ke rumah itu. Kusno menyambut dengan sikap lebih lembut. “Saya salah menilai kalian,” katanya. “Rumah ini butuh kalian.”
Malamnya, setelah pekerjaan selesai, Asmuni memberanikan diri mendekati Erni di teras. Gadis itu tengah menulis di buku harian.
“Erni,” suara Asmuni bergetar. “Aku sadar aku bukan siapa-siapa. Tapi jauh darimu, aku merasa hampa. Aku tidak berani bermimpi terlalu tinggi, tapi izinkan aku menyimpan perasaan ini.”
Erni menutup bukunya, menatapnya dengan mata teduh. “Mas Asmuni… aku tahu. Bahkan sejak lama. Aku juga takut, tapi perasaan tidak bisa disembunyikan. Jangan merasa sendiri.”
Kata-kata itu jatuh bagai hujan pertama setelah musim kemarau. Asmuni menahan air mata, bibirnya tersenyum. Untuk pertama kalinya ia merasa cintanya bukan mimpi kosong.
Di dalam rumah, Kadir mengintip dari balik jendela dan terkekeh pelan. “Ah, Asmuni… akhirnya bintangmu bersinar.”
Jakarta tetap bising, kendaraan tetap melaju, tapi di halaman rumah bercat putih itu, dua hati menemukan jalannya. Roda-roda takdir memang aneh kadang mogok, kadang oleng tetapi akhirnya berhenti tepat di depan pintu hati.
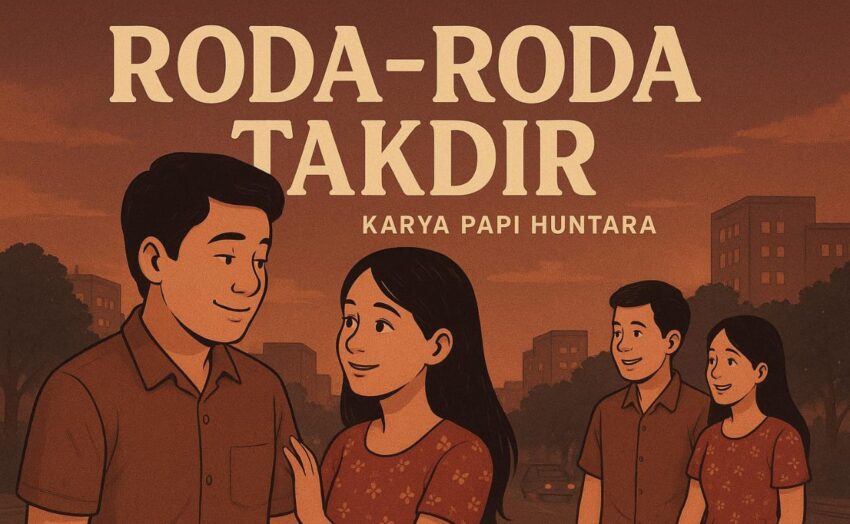
sangat menginspirasi
sya cukup mengerti boy
selalu bersemangat beraktivitas karena roda berputar kadang di bawah kadang di atas .